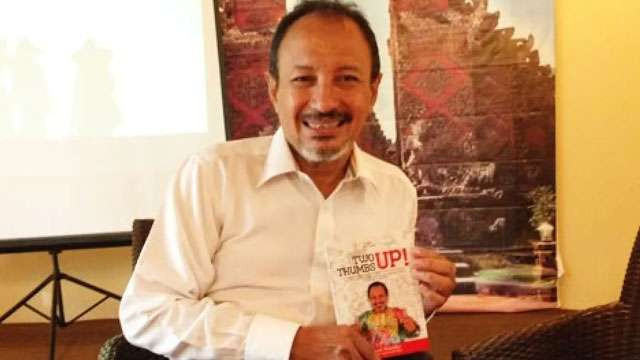Amerika Serikat dan Demokrasi yang Semu

Ketika melihat tayangan di CNN bagaimana polisi Minneapolis menangkap dan memborgol seorang reporter CNN saat live report demonstrasi di kota tersebut, saya langsung bertanya dalam hati.
“Benarkah Amerika (AS) adalah kiblat demokrasi, penegakan HAM, kesetaraan gender, penghormatan terhadap indigenous people, kiblat perang terhadap rasisme, simbol negara yang menyejahterakan rakyatnya, polisi dunia yang menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia?”
Lihat saja bagaimana Polisi New York (NYPD) mengatasi para demonstran. Dua mobil polisi ditabrakkan ke kerumunan massa. Beberapa demonstran ditangkap, diborgol, pun ada yang dibenturkan ke tembok. Ada lagi, seorang wartawan foto yang juga ditangkap. Belum lagi gas air mata, peluru karet, dan pentungan yang dipakai polisi untuk membubarkan demonstran yang menuntut keadilan atas kematian seorang pria kulit hitam George Floyd akibat dicekik dengan kaki oleh seorang polisi kulit putih.
Beginilah cara Amerika menghadapi rakyatnya. Dan rakyat Amerika pun marah, seperti api di dalam sekam yang akhirnya membara. Unjuk rasa, kerusuhan, dan penjarahan terjadi di lebih dari 20 kota di Amerika mulai dari wilayah pantai barat California sampai New York.
Beginilah wajah Amerika yang sesungguhnya. Negara yang sejak usainya Perang Dunia II paling banyak terlibat dalam urusan politik dalam negeri negara lain itu, kini harus sibuk mengatasi kemarahan rakyat mereka sendiri yang menuntut Amerika lebih adil, lebih menyejahterakan, dan menjadi rumah bagi semua ras serta golongan sebagaimana amanah konstitusi mereka.
Rasisme di Amerika
Perbudakan, secara konstitusional, memang sudah dihapuskan di bumi Amerika. Tetapi rasisme tidak pernah benar-benar hilang, pun berdarah-darah. Perang Sipil di Amerika juga dipicu oleh perselisihan antara wilayah yang setuju dengan perbudakan dan wilayah yang ingin menghapuskan isu tersebut dan bergabung dalam sebuah negara bersama yang bersatu: Amerika Serikat. Presiden Abraham Lincoln adalah martir pertama dalam perang melawan rasisme. Pun Presiden JF Kennedy juga ditembak mati karena salah satu alasannya terlalu keras menentang rasisme di negaranya.
Banyak martir lain dalam perang melawan rasisme ini, terutama sikap dan perlakuan pemerintah Amerika terhadap warga kulit hitam (Afrika Amerika). Martin Luther King Jr juga seorang pejuang anti rasialisme yang akhirnya tewas diterjang peluru. Dari kelompok Afrika-Amerika Muslim adalah Malcolm X yang sangat lantang dan terang-terangan menentang diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam. Dengan keterlibatan FBI, Malcolm X juga tewas diberondong peluru. Jika Anda pergi ke wilayah Harlem, pinggiran New York, nama Malcolm X dielu-elukan sebagai pahlawan.
Petinju legendaris Muhammad Ali juga seorang pejuang anti diskriminasi. Kisah Muhammad Ali (sebelumnya bernama Cassius Clay) menjadi seorang mualaf juga didorong oleh perlakuan diskriminatif pemerintah, pun masyarakat Amerika, terhadap masyarakat kulit hitam. Bagaimana mungkin, Clay yang mengharumkan nama Amerika Serikat dengan membawa medali emas Olimpiade dari cabang tinju, di negaranya tetap mendapatkan perlakuan diskriminatif. Tidak bisa duduk di bus dengan bebas, tidak bisa ke toilet umum untuk orang kulit putih, pun tidak bisa beribadah di gereja untuk orang kulit putih.
Belajar dari Elijah Muhammad, pendiri Nation of Islam, Cassius Clay pun mengubah nama menjadi Muhammad Ali dan semakin keras melawan diskriminasi terhadap masyarakat kulit hitam. Ali juga menolak wajib militer ke Vietnam dengan alasan agama Islam melarang umatnya membunuh orang-orang yang tidak berdosa.
“Bagaimana saya mau berperang terhadap orang-orang Vietnam yang saya sendiri tidak tahu apa kesalahan mereka terhadap saya. Sementara ketidakadilan masih banyak kita temui di negara kita sendiri,” tegas Ali.
Terpilihnya Obama sebagai Presiden AS sempat menjadi oase, seperti harapan yang menjadi kenyataan. Barrack Obama menjadi orang kulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika. Dan Obama selama dua periode (8 tahun) telah menunjukkan kelasnya sebagai presiden yang diakui dunia sukses menjaga stabilitas ekonomi, keamanan dan perdamaian tidak saja di dalam negeri AS tetapi juga di dunia.
Banyak orang-orang kulit hitam yang menjadi tokoh politik dan pemerintahan di Amerika. Saat ini misalnya, ada Ilhan Omar, anggota Kongres (Partai Demokrat) mewakili negara bagian Minnesota. Ilhan Omar yang lahir di Mogadishu (Somalia) adalah satu dari dua orang wanita Muslim yang duduk di Kongres (DPR) Amerika. Satunya lagi adalah Rashida Harbi, seorang wanita keturunan Palestina, juga dari Partai Demokrat yang mewakili negara bagian Michigan. Bedanya dengan Ilhan Omar, Rashida lahir di Amerika sehingga dia memiliki peluang maju menjadi calon presiden Amerika.
Obama, Ilhan Omar, dan Rashida Harbi sepertinya adalah harapan bagi masa depan Amerika. Tetapi seperti yang dikatakan Ilhan Omar dalam sebuah acara talk show di TV, “Saya memang harapan (rakyat) Amerika, tetapi saya juga menjadi mimpi buruk bagi Presiden Amerika (Donald Trump).”
Kesetaraan hak antara warga kulit putih dan kulit hitam sepertinya memang masih sekadar etalase daripada benar-benar sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat maupun pemerintah Amerika.
Bias Gender
Dalam Pilpres Amerika Serikat 2016, saya menyampaikan kritik kepada beberapa teman saya yang bekerja di media. Liputan mereka tentang kampanye antara Donald Trump dan Hillary Clinton, terlalu bias. Bias dan terlalu berpihak kepada Hillary, Teman-teman saya tadi sepertinya mengikuti tren pemberitaan TV-TV di Amerika khususnya CNN. Terkesan, Hillary sangat dielu-elukan, Trump dikecam. Hasilnya? Meleset semua. Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 menggantikan Barrack Hussein Obama.
Andaikan saat itu kandidat dari Partai Demokrat adalah seorang laki-laki, sangat mungkin Trump akan kalah. Tetapi karena Partai Demorkat mencalonkan Hillary, meskipun lawannya adalah sosok kontroversial, akhirnya rakyat Amerika tetap memilih Trump. Apalagi dalam sistem Pilpres dengan electoral college di mana popular vote tidak menjamin kemenangan dalam Pilpres, semakin sulit mengalahkan Trump apalagi di wilayah-wilayah yang menjadi basis pendukung Partai Republik.
Selain rasisme, isu lain yang tidak kalah hangatnya di AS adalah bias gender. Meskipun kajian feminisme berasal dari Amerika, namun dalam hal ini Indonesia lebih maju. Indonesia yang baru berusia 75 tahun sudah pernah memilki presiden seorang wanita. Sedangkan Amerika yang sudah merdeka 244 tahun masih menganggap wanita sebagai warga negara kelas dua. Para elite politik, juga banyak masyarakat Amerika, masih berpikiran male chauvinis. Lelaki lebih superior daripada wanita. Sebuah pemikiran kuno yang sudah didobrak RA Kartini pada awal 1900an.
Kita lihat saja data statistik berapa banyak jumlah wanita yang pernah menjadi menteri dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat? Tentu setelah amandemen ke-19 Konstitusi Amerika tahun 1920, karena sebelumnya tidak mungkin seorang wanita bisa menjadi pejabat baik di tingkat negara bagian maupun pada pemerintahan Federal. Sepanjang satu abad tersebut saja, total baru tercatat hanya 32 orang wanita yang pernah menjadi menteri dalam pemerintahan AS.
Pada masa pemerintahan Obama, ada 4 orang wanita yang menjabat menteri, salah satunya adalah Hillary Clinton sebagi menteri luar negeri. Sedangkan pada pemerintahan Trump saat ini hanya ada dua orang menteri wanita yaitu Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan. Kabar baiknya adalah semakin banyak wanita yang duduk di Parlemen Amerika, persentasenya hampir sama dengan Indonesia sekitar 20% dari total anggota Kongres dan Senat.
Amerika Serikat memang tanah impian bagi siapa saja. Tetapi mimpi tidak selalu seindah warna aslinya.
* Tofan Mahdi, praktisi komunikasi. Mantan Wakil Pemimpin Redaksi Jawa Pos dan mantan Pemimpin Redaksi SBO TV Surabaya
([email protected])
Advertisement