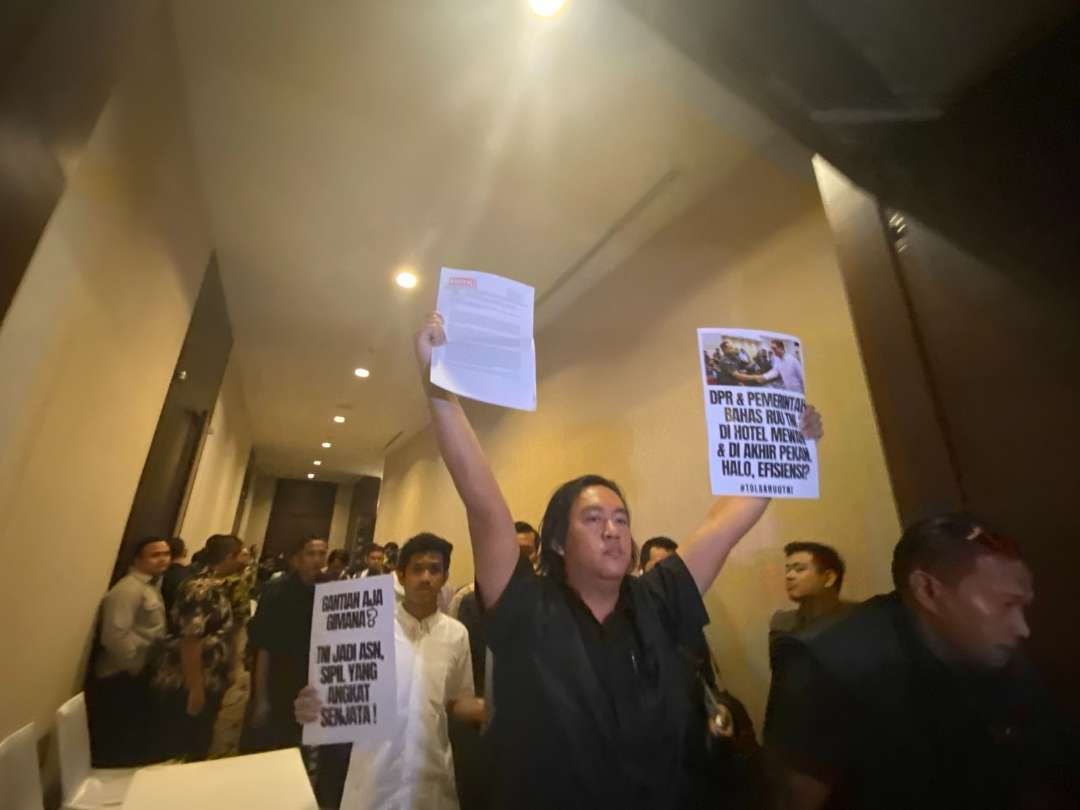Alumni Bukan Partai Politik

Ada yang baru dalam jagat politik Indonesia. Apa itu? Bergeraknya relawan para alumni. Tidak hanya alumni perguruan tinggi. Tapi juga alumni strata pendidikan di bawahnya.
Menarik karena alumni menjadi penggerak politik baru dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Sebuah gelombang gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk pilpres yang mengantarkan Jokowi jadi presiden 4 tahun lalu.
Alumni bukanlah lembaga politik. Ia hanyalah sebutan untuk orang yang pernah mengenyam pendidikan di suatu tempat. Mereka disebut alumni karena lulusan sekolah, akademi dan perguruan tinggi. Alumni bukan organisasi. Tapi label yang melekat pada seseorang.
Lalu bagaimana alumni bisa menjadi identitas baru untuk sebuah gerakan politik? Akankah mereka bisa menjadi arus baru gerakan politik yang bisa melahirkan kepemimpinan di negeri ini? Lantas bagaimana dengan partai politik? Apakah ini merupakan arus baru yang baik bagi politik Indonesia.
Saya tentu tidak bisa menjawab dengan tepat. Tapi setiap lahirnya aktor-aktor politik baru di luar partai politik, sepantasnya menjadi lampu kuning. Menjasdi peringatan. Menjadi deteksi dini bagi politik di negeri ini. Setidaknya menjadi lampu kuning bagi partai politik.
Sudah sejak lama memang. Sejak adanya pemilihan langsung lima tahun sekali. Pemilihan langsung pada akhirnya lebih banyak tergantung figur kandidat. Bukan pada partai pengusungnya. Bukan tergantung kepada partai yang menggotongkannya.
Partai hanya menjadi semacam ojek. Hanya seperti oplet --kalau masih ada yang ingat moda transportasi ini. Hanya seperti bus, kereta api, dan pesawat. Partai hanya menjadi ''pemberi'' tiket kandidat untuk bertarung menjadi kepala daerah maupun presiden.
Peran ''pemberi'' tiket ini memang sesuai dengan undang-undang. Setiap calon kepala daerah, dan juga presiden harus diusung partai politik yang minimal punya kursi 20 persen di parlemen. Kalau tidak cukup 20 persen, maka partai bisa berkoalisi dengan partai lain.
Memang ada partai yang tidak hanya menjadi pemberi tiket. Namun, partai itu secara sengaja didirikan untuk mengusung kandidat. Juga didirikan oleh sang kandidat sendiri. Misalnya Partai Demokrat yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto.
Partai-partai lama umumnya tidak bisa menjadi pemberi tiket sekaligus mesin politik bagi calonnya. Karena kedua partai itu didirikan sebagai kendaraan menuju kursi kepresidenan, maka ia didesian sejak awal juga menjadi mesin politik. Untuk pemenangan calon presiden yang memang pendiri partai tersebut.
Partai Demokrat telah dua kali sukses menjadi pengusung sekaligus mesin politik pendirinya. Bahkan, sempat menjadi pemenang pemilu saat pendirinya berhasil menjadi orang pertama di negeri ini. Meski kemudian partai tersebut menyusut kembali setelah tak berkuasa.
Singkatnya, partai politik tak selalu efektif menjadi mesin politik untuk pemilihan presiden maupun kepala daerah. Kekuatan figur personal kandidat sering lebih menentukan ketimbang kekuatan mesin partai politik. Apalagi ketika kandidat bukan pemimpin puncak partai tersebut.
Fenomena ini terjadi pada Joko Widodo. Calon presiden yang diusung PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan PSI ini bukan pemimpin partai dari pengusungnya. Ia hanya seperti ''pembeli'' tiket parpol untuk mengusungnya. Soal pemenangan menjadi urusan yang lain lagi.
Saat pilpres yang mengantarkan kemenangan kali pertamanya, Jokowi mengandalkan relawan sosmed yang militan. Para relawan tanpa identitas jelas. Mereka yang seperti muncul tiba-tiba. Mereka yang terpesona dengan tampilnya mantan Walikota yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Juga lahirnya cyber army dalam pertarungan presiden kali pertama. Ia punya banyak die hard di dunia maya. Ia berhasil menarik para buzzer medsos yang menjadi pengganda dan penyebar pesan-pesan politiknya. Mereka itu menjadi semacam gelombang politik baru penentu kemenangan kandidat di Indonesia.
Pertarungan cyber army masih juga berlangsung sampai sekarang. Tidak hanya pasukan Jokowi, Prabowo pun punya pasukan yang tidak kalah dahsyat. Dunia maya sudah sejak lama menjadi ladang kuruseta, killing field, dan ajang pertarungan hebat antar pasukan keduanya. Dari pertarugan dunia maya inilah hoaks, ujaran-ujaran kebencian, dan fitnah berseliweran.
Tentu tidak selalu keberhasilan diulang dengan cara yang sama. Sebab, setiap keberhasilan selalu menginsipirasi yang lain untuk menirunya. Siapa pun yang terbiasa berkontestasi akan tak menggunakan cara yang sama untuk memperoleh keberhasilan keduanya. Karena kalau sama dengan sebelumnya tak terlalu terlihat pembedanya.
Lahirnya gelombang gerakan alumni sebagai jaringan relawan baru Jokowi menarik disimak. Ia tiba-tiba saja muncul mewarnai pilpres 2019. Ia menjadi kekuatan baru ketika para relawan Jokowi sebelumnya tak lagi tampil militan. Sebab, sebagian besar dari mereka sudah pada posisi mapan.
Memanfaatkan jaringan alumni bisa dianggap sebagai kecerdikan baru dalam politik. Saat partai politik pengusungnya tak bisa diharapkan menjadi mesin andalan. Ketika partai politik pengusungnya harus menghadapi peperangan hidup dan mati dalam pemilu serentak.
Namun, fenomena ini menjadi pedang bermata dua bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Apa pun partai politik adalah institusi formal yang diharapkan menjadi pilar utama demokrasi. Ia diharapkan tidak hanya menjadi agregrator kepentingan, tapi juga tempat kaderisasi kepemimpinan politik.
Ketika sumber kepemimpinan tak lagi bertumpu pada parpol, maka perannya dalam memperkokoh demokrasi menjadi berkurang. Bahkan, bisa saja mereka menjadi benalu politik yang kurang diminati. Di saat demikian, ia menjadi tempat berlabuhnya orang-orang yang kurang berkualitas sehingga berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan politik.
Tampilnya barisan alumni sebagai gerakan politik baru pada akhirnya akan mendelusi kualitas demokrasi di masa mendatang. Karena itu, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana partai menjadikan fenomena ini sebagai bahan evaluasi diri.
Partai politik harus tetap menjadi pilihan utama sebagai penyalur aspirasi kepentingan sekaligus tempat rekrutmen kepemimpinan politik di masa depan. Tak boleh puas hanya sebagai penjual tiket bagi kepemimpinan nasional. (Arif Afandi)
Advertisement