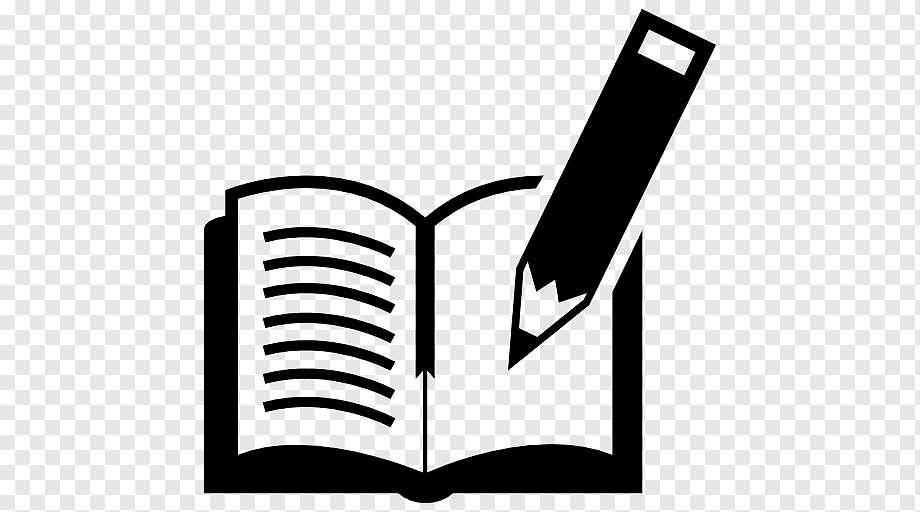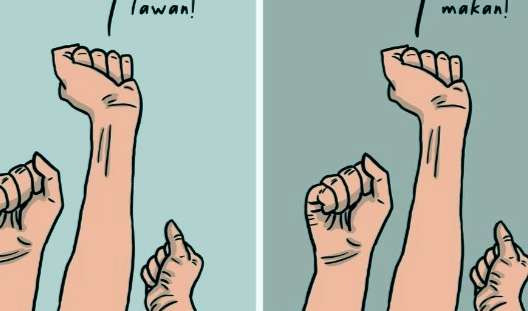7 Catatan! Gus Dur dan Cak Nur, Inspirasi Kebangsaan

Di tengah silang sengkarut persoalan kebangsaan dalam kehidupan bernegara kita, kita semakin ruwet dengan komentar banyak orang yang sebenarnya tak kompeten pada masalah tertentu. Bila disadari permasalahan sesungguhnya, mereka lebih banyak berisik tanpa ilmu.
Namun, kehadiran tokoh-tokoh cendekiawan dan tokoh agama pada masa lalu, bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita kini. Eksistensi KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nucholish Madjid (Cak Nur) —almaghfurlahum— tak mati meski keduanya telah wafat. Karena pemikiran dan renungannya yang jernih untuk kehidupan sosial kemasyarakatan kini.
Pandangan menarik bertajuk “Ketika Anda Berpikir, Anda Berfilsafat”, yang merupakan Percakapan Gita Wirjawan dan Budhy Munawar Rachman mencoba menjenihkan permasalahan kehidupan kita. Berikut catatan lengkapnya (Redaksi).

Di tengah dinamika kehidupan modern, Gita Wirjawan dan Budhy Munawar Rachman mengajak kita untuk menyelami pemikiran mendalam tentang filsafat, pendidikan, dan peran keterbukaan dalam menghadapi tantangan zaman. Percakapan mereka menyiratkan bahwa setiap tindakan berpikir—bahkan ketika bertanya “kenapa?” seperti yang sering dilakukan anak kecil—adalah bentuk berfilsafat.
Dari sini, terungkap betapa pentingnya mengasah kemampuan berpikir kritis sejak dini melalui pendidikan yang bukan hanya menghafal, melainkan menginvestigasi dan merangkai ide.
1. Filsafat dalam Kehidupan Sehari-hari
Menurut Budhy Munawar Rachman, filsafat bukanlah ilmu yang terpisah dari kehidupan, melainkan bagian integral dari aktivitas sehari-hari. “Ketika kita mulai berpikir, kita sebenarnya sudah berfilsafat,” ujarnya.
Dalam pandangannya, filsafat mencakup pendekatan logika, metafisika, dan epistemologi yang melekat dalam cara kita mengamati dan menafsirkan dunia. Bahkan pertanyaan sederhana yang dilontarkan anak kecil mencerminkan bakat filosofis yang telah ada sejak lahir.
2. Pendidikan dan Pengembangan Critical Thinking
Salah satu topik utama dalam dialog ini adalah peran pendidikan—khususnya pengajaran filsafat—dalam membentuk pemikiran kritis. Budhy menekankan pentingnya peran guru, yang jika mampu mengintegrasikan unsur-unsur filsafat dalam bidang studi masing-masing, dapat “memicu proses imajinasi” dan mengasah kemampuan berpikir analitis siswa.
Ia mengamati bahwa di banyak sekolah, pola pendidikan masih cenderung menghafal dan kurang memberi ruang untuk diskusi serta kritik mendalam.
Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya perombakan dalam kurikulum dan, yang lebih penting, peningkatan kualitas serta pemilihan guru yang mampu menanamkan semangat berpikir kritis sejak dini.
3. Filsafat dan Agama: Dialog yang Menggairahkan
Percakapan ini juga mengulas hubungan antara filsafat dan agama, terutama dalam konteks pemikiran Islam. Budhy mengungkapkan bahwa filsafat dan wahyu tidak selalu berada dalam pertentangan. Dalam sejarah pemikiran Islam, perdebatan tentang hubungan antara akal dan wahyu telah melahirkan karya-karya besar, mulai dari tokoh-tokoh seperti Alfarabi, Ibn Sina, hingga Al-Ghazali.
Walaupun sempat terjadi konflik—di mana filsafat sempat dianggap bertentangan dengan ajaran agama—pemikiran-pemikiran kritis justru membuka jalan bagi dialog konstruktif yang menghasilkan sintesis antara rasionalitas dan keimanan. Hal ini menjadi contoh bahwa keterbukaan intelektual bisa mendorong kemajuan dalam memahami hakikat eksistensi dan nilai-nilai keagamaan.
4. Tantangan di Era Digital dan Kritis dalam Pendidikan
Di era media sosial dan digital, Budhy dan Gita juga menyoroti dampak teknologi terhadap proses berpikir generasi muda. Dengan penggunaan gadget yang intensif, terdapat kekhawatiran bahwa kualitas pemikiran kritis dan spiritualitas dapat tereduksi.
Tantangan saat ini adalah bagaimana mengarahkan penggunaan teknologi dan internet agar dapat memperkaya pengetahuan, mendorong dialog terbuka, dan meningkatkan literasi—bukan sekadar konsumsi konten yang dangkal. Dalam konteks ini, peran guru dan lembaga pendidikan semakin krusial untuk melatih siswa agar mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dan pengembangan kapasitas berpikir kritis.
5. Menyatukan Nilai-Nilai Pancasila dan Keterbukaan
Sebagai negara dengan keberagaman budaya, etnis, dan agama, Indonesia dituntut untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebinekaan. Percakapan antara Budhy dan Gita menggambarkan betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan demokrasi substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mereka menekankan bahwa keberhasilan sebuah sistem demokrasi tidak hanya diukur dari distribusi kekuasaan, tetapi juga dari kemampuan mendemokratisasikan talenta, memastikan pemerataan pendidikan, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif.
6. Inspirasi dari Tokoh-Tokoh Pemikir
Dalam perbincangan ini, beberapa tokoh besar seperti Cak Nur (Nurcholis Madjid), Gus Dur, dan tokoh-tokoh pesantren disebut sebagai inspirasi yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran keagamaan dan politik di Indonesia.
Pemikiran mereka —yang mendorong keterbukaan, dialog, dan penerimaan terhadap perbedaan— menjadi landasan penting untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan politik yang ada. Semangat inilah yang diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menggali ilmu dan mengembangkan cara berpikir yang inovatif.
7. Kesimpulan
Percakapan antara Gita Wirjawan dan Budhy Munawar Rachman merupakan refleksi mendalam mengenai bagaimana filsafat hadir dalam setiap aspek kehidupan. Dari pendidikan, keagamaan, hingga tantangan di era digital, dialog mereka mengingatkan kita bahwa kemampuan berpikir kritis dan terbuka adalah modal utama untuk kemajuan peradaban.
Dengan mengintegrasikan nilai-nilai filsafat dalam sistem pendidikan dan kehidupan sehari-hari, serta mengadopsi semangat keterbukaan dan dialog, Indonesia—sebagai negara yang kaya akan keberagaman—dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan beradab.
Silakan klik: https://www.youtube.com/watch?v=y8--XlKXCJY...
Advertisement